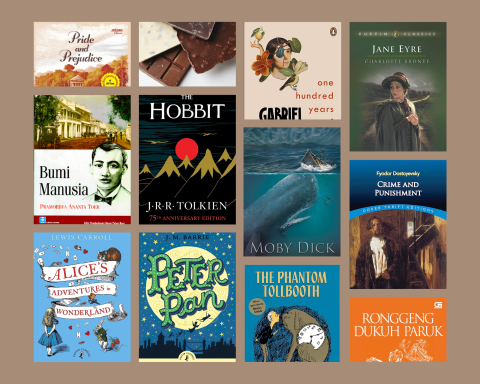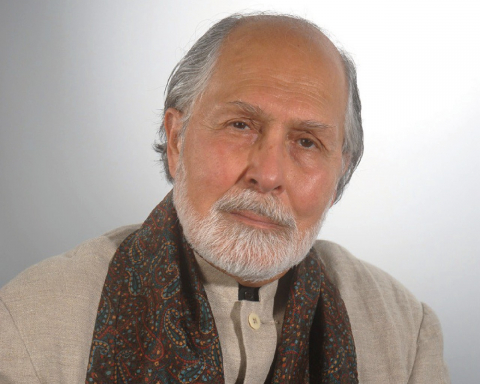Ketika 2020 menjelang fana, berikut ini kami sajikan sejumlah pengarang dan penulis yang telah abadi pada tahun ini. Daftar ini tentu saja tak berpretensi menjadi lengkap.
MANUSIA datang dan pergi. Tak ada yang abadi. Hanya detik waktu yang tinggal. Tidak. Kata Sapardi Djoko Damono dalam puisinya, yang fana adalah waktu. Justru manusia yang mampu merangkai detik demi detik akan abadi.
Ketika 2020 menjelang fana, berikut ini kami sajikan sejumlah pengarang dan penulis yang telah abadi pada tahun ini. Daftar ini tentu saja tak berpretensi menjadi lengkap. Kami memilihkan beberapa nama yang kami anggap berperan dalam dunia kepengarangan di Tanah Air. Peran mereka dikenal, baik melalui karya maupun aktivitas. Kami juga menambahkan dua nama dari luar negeri—yang karya-karya mereka ikut mewarnai kehidupan kita–setidaknya menurut kami.
Arief Budiman (Wafat 23 April 2020)
Orang lebih mengenal Arief Budiman (79 tahun) sebagai akademisi, pengamat sosial-politik, dan aktivis di era 1960-an—bersama saudaranya Soe Hok Gie. Mungkin sedikit orang yang mengetahui kiprahnya di dunia kesusastraan. Profesor di University of Melbourne, Australia, ini setidaknya berperan dalam dua perdebatan kesusastraan yang menelurkan dua gagasan.
Pertama, dia terlibat perdebatan dengan para sarjana sastra Universitas Indonesia soal kritik sastra pada 1968. Kelompok yang terakhir ini mengusung metode kritik sastra akademik, berlandaskan pada teori-teori sastra yang rigid dan berfokus hanya pada karya sastra—mereka kemudian disebut aliran kritik sastra Rawamangun (lokasi Fakultas Sastra UI pada saat itu).
Arief Budiman, bersama sejumlah nama lain, menepis kecenderungan kritik sastra seperti itu. Dia mengajukan gagasan, yang kemudian disebutnya dengan metode kritik sastra Ganzheit. Metode ini berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmu psikologi Gestalt (Arief sendiri lulusan Fakultas Psikologi UI). Arief merumuskan bahwa kritik sastra Ganzheit adalah proses partisipasi aktif kritikus terhadap karya sastra.
“…sang kritikus membiarkan karya seninya berbicara sendiri kepada mereka. Kemudian, terjadilah sebuah dialog, sebuah pertemuan, sebuah inferensi dinamik antara kedua subjek yang hidup dan merdeka itu.”
Metode kritik sastra Ganzheit sebenarnya jalan tengah antara dua kubu ekstrem kritik sastra: objektif versus subjektif. Kritik sastra objektif lebih menekankan kajian atas karya pada unsur-unsur intrinsiknya, tak memedulikan elemen-elemen di luar itu (pengalaman hidup pengarang dan latar sosial-politik penciptaan). Sebaliknya, kritik subjektif menganalisis karya sesuka hati berdasarkan pengalaman kritikus dan menolak apa yang dianggap sebagai “ukuran universal”.
Dalam kritik Ganzheit, Arief mengajukan gagasan dialog antara karya seni dengan kritikusnya. Tidak ada subjek-objek, tapi subjek-subjek. Dari dialog inilah, akan lahir sebuah pengalaman kesusastraan baru, yang berbeda dan unik antara satu kritikus dengan kritikus lainnya sehingga memperkaya pembacaan.
Kedua, Arief, bersama Ariel Heryanto, mengusung gagasan “sastra kontekstual” pada 1984. Gagasan ini lahir karena keduanya melihat kecenderungan universalisasi ekstrem terhadap apa yang bisa disebut sebagai “sastra” atau “bukan sastra”. Kecenderungan ini membuat para pengarang Indonesia lebih memilih gaya dan tema kebarat-baratan ketimbang menyuarakan pengalamannya dan pengalaman bangsanya sendiri. Kecenderungan itu juga melahirkan apa yang disebut “tirani sastra kelas menengah-kota”.
Masih konsisten dengan metode kritik sastra Ganzheit, Arief Budiman berpendapat nilai-nilai kesusastraan sangat ditentukan oleh waktu, tempat, dan lingkungan masyarakatnya. Mengabaikan hal-hal ini, bagi Arief, sama saja dengan mengebiri kemajuan dan perkembangan sastra.
Selain berperan dalam gagasan, Arief Budiman juga aktif di organisasi kesusastraan, dan kebudayaan pada umumnya. Dia ikut mendirikan majalah sastra Horison dan menjadi redaktur majalah ini (1966-1972). Dia juga pernah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (1968-1971).
Sapardi Djoko Damono (Wafat 19 Juli 2020)

Bagi Anda penggemar puisi, nama ini tentu sudah tak asing lagi. Ya, Sapardi Djoko Damono (80 tahun), salah satu perintis puisi lirik di Indonesia. Namanya bahkan kini tenar di kalangan milenial saat puisi-puisinya dibuat lagu dan film—ini salah satu kelebihan puisi lirik.
Sejak usia belasan hingga akhir hayatnya, Sapardi tak berhenti menulis puisi. Uniknya, Sapardi memutuskan menulis puisi setelah ceritanya ditolak redaksi sebuah majalah anak-anak dengan alasan tak masuk akal. Sapardi kemudian mendapati bahwa dunia tak masuk akal lebih bisa diterima oleh puisi ketimbang prosa.
Dalam puisi-puisinya, Sapardi lebih berbicara tentang tema personal manusia daripada tema sosial yang digandrungi banyak penyair pada masanya. Puisi-puisinya menyuarakan kepedihan, kecintaan, kerinduan, dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia. Saat mencoba menggubah puisi-puisi bertema sosial dalam kumpulan Ayat-Ayat Api (2000), dia malah mendapat kritik negatif. Nada puisi dalam kumpulan ini dianggap tak khas “Sapardi”.
Dari kumpulan-kumpulan puisinya, Hujan Bulan Juni (1994) bisa dibilang yang paling dikenal orang. Kumpulan puisi ini menginspirasi sejumlah musisi dan sineas untuk membuat lagu dan film.
Kesuksesan dalam karir kepengarangan berbanding lurus dengan pencapaian Sapardi di dunia akademik. Selain menulis non-fiksi tentang puisi, sastra, dan kebudayaan, Sapardi dipilih sebagai dekan Fakultas Sastra UI (1995-1999). Meskipun gelar sarjana diperolehnya dari Fakultas Sastra UGM, Sapardi menyelesaikan pendidikan doktoral dan mendapat gelar profesor dari UI. Pantaslah kiranya ketika Bakdi Soemanto, dalam Sapardi Djoko Damono: Karya dan Dunianya, menyebut sang penyair sebagai “profesor para penyair Indonesia”.
Ajip Rosidi (Wafat 29 Juli 2020)

Ajip Rosidi (82 tahun) adalah salah satu—jika bukan satu-satunya—sastrawan paling lengkap. Dia mengarang, menyunting, menerjemahkan, dan mengarsip. Dia melintasi bentuk karangan: puisi, cerpen, novel, drama, dan bahkan cerita anak-anak. Dia bersastra dalam dua bahasa dengan sama bagusnya: Indonesia dan Sunda.
Dia juga produktif. Lampiran memoarnya mencatat sembilan kumpulan puisi, lima kumpulan cerita pendek, dua novel, dua drama, delapan adaptasi cerita rakyat, dua cerita wayang, lima cerita anak-anak, dua kumpulan humor, tiga memoar, tiga biografi, dan 52 kumpulan esai dan kritik sastra. Itu belum termasuk karya-karya ensiklopedia, terjemahan, dan hasil penelitian. Dia masih menyimpan banyak tulisan, arsip, dokumen, dan catatan harian yang belum diterbitkan.
Istimewanya, semua pencapaian itu dimulai sejak usia dini dan tanpa ijazah pendidikan tinggi. Pada usia 15 tahun, Ajip sudah mengasuh majalah Soeloeh Peladjar. Pada usia 17 tahun, dia menjadi redaktur majalah Prosa.
Cuma jebolan sekolah menengah Taman Siswa, Ajip justru mengajar dan menjadi guru besar di sejumlah universitas, baik di dalam maupun luar negeri. Saat mengajar di Jepang, Ajip-lah yang pertama kali memperkenalkan karya pengarang-peraih Nobel Jepang, Yasunari Kawabata, dengan menerjemahkan kumpulan cerpen Penari-Penari Jepang dan Negeri Salju.
Tak hanya bersastra, Ajip juga mendirikan dan mengelola penerbit serta lembaga kebudayaan. Dia membidani Yayasan Kebudayaan Rancage, yang antara lain memberi hadiah sastra kepada karya-karya “bahasa ibu” (Ajip tak suka menggunakan istilah “bahasa daerah”), antara lain bahasa Sunda, Jawa, Bali, Lampung, Batak, Banjar, dan Madura. Perannya juga cukup besar dalam mengembangkan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Dewan Kesenian Jakarta, Akademi Jakarta, dan Ikatan Penerbit Indonesia.
Mary Higgins Clark (Wafat 31 Januari 2020)

Dari mancanegara, langsung teringat satu nama, yaitu Mary Higgins Clark (92 tahun), pengarang asal Amerika Serikat. Jika mengunjungi toko buku, Anda akan bisa langsung mengenali novel-novel Mary dari kejauhan. Sampulnya didesain dengan warna-warna menyala dan tipografi nama Mary berukuran lebih besar dan indah daripada judulnya.
Mary adalah salah satu ratu suspens di dunia. Dia telah menghasilkan 50 judul novel, dan setiap judulnya laku keras, alias menjadi bestseller, terutama di Amerika dan Eropa. Novel suspens pertamanya, Where Are the Children, yang ditulis pada 1974 bahkan masih dicetak ulang hingga 2015.
Mary pada awalnya berkarir sebagai kopieditor dan kemudian pramugari di maskapai Pan-America. Setelah menikah dan meninggalkan pekerjaannya, Mary membantu keluarga dengan menulis cerita-cerita pendek dan naskah drama radio.
Pada 1968, setelah didorong oleh orang-orang untuk menulis novel, Mary menghasilkan Aspire to the Heavens, novel tentang kisah salah satu bapak bangsa Amerika, George Washington. Tapi, buku ini jeblok dari sisi komersial.
Di titik itulah, Mary berpikir untuk menulis apa yang dia suka, apa yang dekat dengan hati dan pikirannya, yakni suspens dan misteri. Dan, pilihan ini tepat. Benarlah kata sutradara kenamaan, Martin Scorsese, bahwa yang paling personal itulah yang paling kreatif.
John Le Carre (Wafat 12 Desember 2020)

Kita mengenalnya sebagai John Le Carre (89 tahun), tapi itu ternyata nama pena. Nama aslinya David John Moore Cornwell. Lebih jauh, kita mengenalnya sebagai penulis novel-novel spionase yang banyak diadaptasi ke layar lebar. Sebut saja beberapa di antaranya: Our Kind of Traitor, A Most Wanted Man, Tinker Tailor Soldier Spy, dan The Constant Gardener.
Sebelum memutuskan menjadi penulis, Le Carre adalah agen intelijen Inggris (M16) pada 1960-an, atau ketika Perang Dingin tengah berada di titik beku. Ini mungkin mengapa novel-novelnya banyak bercerita tentang agen mata-mata Inggris dengan latar Perang Dingin (1945-1991).
Karakter “hero” andalan Le Carre adalah George Smiley, yang muncul sebagai tokoh utama pada lima novel dan pendukung pada beberapa novel lain. Uniknya, Smiley seperti diciptakan Le Carre sebagai antitesis terhadap karakter Ian Fleming, James Bond—Le Carre sendiri menyatakan Bond lebih tepat disebut sebagai gangster internasional daripada agen mata-mata. Smiley misalnya tidak banyak berkelahi dan kejar-kejaran dengan musuh. Dia juga tak digambarkan ganteng, menggoda, dan bertubuh atletis. Smiley justru bertampang seorang birokrat kantoran berkaca mata tebal dan kelebihan berat badan, yang menyelesaikan kasus dengan kecerdasan dan kelicikannya.
Dalam novel-novelnya, Le Carre juga tidak menahbiskan Smiley sebagai “hero” dan pemerintahan Barat sebagai yang paling bermoral dalam perang spionase tersebut. Tokoh-tokoh Le Carre seringkali malah meragukan dan bahkan mempertanyakan nilai-nilai Barat yang mereka harus lindungi sebagai agen negara. Tokoh-tokohnya selalu berada dalam ambiguitas moral ketika menjalankan misi mereka.[]