Serial Bridgerton memilih menampilkan duke berkulit hitam. Pernahkah ada bangsawan berkulit gelap di era Regency? Seberapa pentingkah akurasi historis bagi fantasi?
NETFLIX meluncurkan serial terbaru, Bridgerton, pada akhir 2020. Serial ini menjanjikan banyak hal menarik. Salah satu produser sekaligus kreatornya, Chris Van Dusen, pernah menggarap serial berkualitas seperti Grey’s Anatomy dan Scandal. Skenarionya diadaptasi dari delapan seri novel Julia Quinn yang terjual lebih daripada 10 juta kopi. Season pertama serial ini menampilkan seluruh novel seri pertama yang berjudul The Duke and I (2000). Kabarnya, Shonda Rhimes, produser lainnya dan pemilik rumah produksi Shondaland (juga memproduksi Grey’s Anatomy dan Scandal), akan memfilmkan keseluruhan seri novel itu. Maka, bisa diperkirakan akan ada setidaknya delapan season.
Cerita novel serial Bridgerton berpusat pada Bridgerton, keluarga kalangan atas di Inggris pada masa Regency, sebutan untuk periode sejarah di akhir kekuasaan Raja George III ketika Sang Raja mengalami sakit jiwa dan untuk sementara digantikan anaknya sebagai Pangeran Pemangku Raja (Prince Regent), atau sekitar 1811 hingga 1820. Quinn memang pengarang spesialis fiksi romansa periode sejarah, terutama di Inggris, meskipun lahir dan besar di Amerika Serikat.

- Judul Film: Bridgerton (Serial)
- Kreator: Chris Van Dusen
- Produsen: Chris Van Dusen, Shonda Rhimes
- Pemain: Adjoa Andoh, Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Claudia Jessie, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel
- Rilis: 25 Desember 2020 (Netflix)
- Durasi: 1 Season, 8 Episode (57-72 menit)
Di Season Pertama, kita disodori tradisi kaum bangsawan Inggris terkait dengan perempuan dan pernikahan. Pada masa itu, perempuan-perempuan muda siap nikah bak dipasarkan di sebuah perjamuan kerajaan, ke hadapan Ratu Charlotte. Mereka yang mendapatkan restu Sang Ratu bakal cepat mendapatkan pasangan sementara yang tidak akan menghadapi kemungkinan mengerikan: melajang sampai tua. Karena itu, sejak lahir, seorang perempuan bangsawan benar-benar dipersiapkan untuk satu momen itu.
Terhadap tradisi ini, Bridgerton menyajikan gugatan kecil. Misalnya, Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), sulung perempuan dari keluarga terpandang itu, mengatakan seluruh hidup perempuan hanya dinilai pada satu momen perjodohan itu. Jika gagal, perempuan tak bernilai, hanya seorang perawan tua sekalipun seorang Bridgerton.
“Kau tak tahu rasanya menjadi wanita, seperti apa rasanya saat seluruh hidupmu hanya dinilai dari satu momen. Aku dibesarkan hanya untuk ini. Inilah diriku. Aku tak punya nilai lain. Jika tak bisa menemukan suami, aku tak berguna.”
Lalu, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), putri kedua dan anak kelima, yang berkarakter pemberontak serta rasional mengatakan, “Berwajah elok dan berambut bagus bukan suatu capaian. Kau tahu yang merupakan capaian? Menuntut ilmu di universitas. Jika pria, aku bisa lakukan itu. Aku justru harus berdiri dan melihat ibuku tampak bangga karena pria mau mengagumi wajah dan rambut saudariku lalu menghamilinya.”
Status sosial perempuan pada masa itu lebih rendah daripada pria di kelas sosial yang sama. Orang hanya akan percaya fakta jika yang berbicara adalah pria. Di sini, Bridgerton menampilkan sosok Lady Whistledown (Julie Andrews), penulis anonim selembaran gosip yang beredar luas di London, sebagai antitesis. Kata-kata yang ditulis Lady Whistledown tak hanya memengaruhi kaum pria tapi bahkan juga kerajaan.
Namun, serial ini memantik pertanyaan—dan bahkan kontroversi—ketika memilih aktor kulit hitam untuk memerankan dua karakter bangsawan utamanya, Simon Basset atau Duke of Hastings (Regé-Jean Page) dan Lady Danbury (Adjoa Andoh). Pertanyaannya, benarkah ada seorang duke (adipati), penguasa sebuah wilayah setara kadipaten di Indonesia pada masa kolonial, atau lady di Inggris berkulit hitam? Benarkah kaum bangsawan kulit putih di Inggris pada masa itu bisa menerima kulit hitam sederajat dengan mereka?
Sejarah ternyata mencatat seorang duke berkulit hitam atau setidaknya berkulit gelap. Namanya Alessandro de’ Medici. Dia Duke of Firenze (atau Florence) di Italia. Riwayat hidup Alessandro sangat menarik. Asal-usulnya kontroversial. Kekuasaannya dikelilingi konspirasi. Dan, ia mati dibunuh sepupunya sendiri di usia 26 tahun.
Sebagian besar sejarawan, seperti Joel A Rogers dalam The World’s Great Men of Color, menyebut Alessandro berasal dari rahim seorang ibu Afrika, yang menjadi budak-pelayan di rumah sebuah dinasti politik di Firenze: keluarga Medici. Budak perempuan itu, Simonetta da’ Collevecchio, dipaksa melepaskan hak atas anaknya dengan hadiah kebebasannya. Cara bangsawan Eropa memperlakukan budak perempuan yang melahirkan “anak haram” mereka seperti ini lazim terjadi (pengarang Kamila Shamsie menggambarkannya dalam cerpen “Biadab” yang telah kami terjemahkan). Mereka biasanya membebaskan budak perempuan itu atau menjualnya ke pasar budak. Yang terpenting, si budak tak mengklaim anak itu sebagai anaknya.
Karena asalnya yang campuran, pelukis-pelukis Italia dari era Renaisans, seperti Bronzino dan Pontormo, menggambarkan Alessandro sebagai seorang mulatto (sebutan orang Eropa untuk keturunan campuran). Alessandro berkulit gelap, berambut keriting, dan berbibir tebal. Lukisan-lukisan Alessandro dan catatan-catatan sejarah membuat sejarawan yakin Alessandro memang seorang mulatto. Karenanya, ia dijuluki “The Moor” (Moor merupakan sebutan Kristen Eropa kepada Muslim keturunan Afrika yang hidup di Semenanjung Iberia, seperti Portugal dan Spanyol pada Abad Pertengahan).
Sejarawan lain—meskipun hanya sebagian kecil—menganggap penisbatan Alessandro kepada seorang ibu budak Afrika hanyalah rumor yang disebarkan oleh musuh-musuhnya. Alessandro memang memiliki banyak musuh. Dia berkuasa represif. Joel A Rogers menyebutnya seorang tiran, apalagi Dinasti Medici naik takhta dengan memberangus aspirasi kaum republikan.
Namun, sejarawan yang meyakini Alessandro adalah seorang mulatto menduga asal-usul Sang Duke sengaja disembunyikan karena tak sedikit keluarga bangsawan Eropa yang memiliki garis keturunan langsung kepada Alessandro. Jika ini diketahui publik, reputasi keturunan dan klaim mereka akan kekuasaan serta wilayah akan ternoda.
Bukan hanya ibu Alessandro yang kontroversial, tapi juga ayahnya. Meskipun bersepakat bahwa Alessandro merupakan anggota Dinasti Medici, sejarawan berdebat tentang siapa figur ayah Alessandro. Apakah ia Lorenzo II de’ Medici, Sang Patriakh dari keluarga ini, ataukah Giulio de’ Medici, Kardinal Firenze yang kemudian menjadi Paus Klemens VII.
Secara resmi, Lorenzo mengakui Alessandro sebagai anaknya. Tapi, gosip menggunjingkan bahwa Giulio adalah ayah Alessandro karena Sang Paus mengambil risiko untuk mendukung dan melindungi kekuasaan Alessandro. Dukungan Paus Klemens VII kepada Charles V of Habsburg sebagai Kaisar Imperium Romawi Suci menghadiahkan gelar duke dan kekuasaan di Firenze bagi Alessandro. Paus Klemens VII secara definitif memilih sendiri Alessandro di antara banyak anggota lain klan Medici. Inilah yang menimbulkan kecemburuan sepupu-sepupu Alessandro, sehingga salah seorang di antaranya, Ippolito, kemudian membunuhnya.
Sebagai selingan, Dinasti Medici sangat terkenal dan berpengaruh di Firenze pada masa Renaisans. Alessandro sendiri adalah cucu langsung dari Lorenzo de’ Medici, yang dijuluki “The Magnificent”. Niccolo Machiavelli mendedikasikan masterpiece-nya, The Prince, kepada Lorenzo “The Magnificent” pada 1513.
Kontroversi asal-usul juga terjadi pada Ratu Charlotte, yang dalam serial Bridgerton diperankan aktris teater Golda Rosheuvel. Ketika pertama kali menyaksikan sosok Sang Ratu di episode pertama, kita mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana bisa sosok berkulit gelap duduk anggun di atas singgasana seraya menerima penghormatan dari para lady dan lord berkulit putih? Permaisuri Raja George III (George “Si Raja Gila” dalam arti denotatifnya) itu disebut memiliki darah bangsa Moor dari keluarga besarnya di Portugal meskipun persoalan ini baru diperdebatkan seratus tahun kemudian. Klaim bahwa Charlotte memiliki ras campuran tak sekuat klaim serupa atas Alessandro meskipun kontroversi Charlotte terus berlanjut hingga kini. Jika klaim atas Charlotte benar, tentu saja keturunannya, seperti Ratu Victoria dan bahkan Ratu Elizabeth II saat ini, memiliki darah Afrika.
Apa yang bisa kita pelajari dari kontroversi Alessandro de’ Medici? Pertama, ternyata pernah ada duke di Eropa yang berasal dari kulit berwarna—setidaknya itu kesepakatan mayoritas sejarawan. Kedua, mobilitas vertikal kulit berwarna di Eropa lebih disebabkan oleh persetubuhan di luar pernikahan—jika kita tak ingin mengatakannya sebagai percintaan. Ketiga, membaca kontroversi asal-usul Alessandro, dan kemungkinan motif di baliknya, tampak bahwa masyarakat elite di Eropa belum bisa menerima keberadaan seorang bangsawan berkulit gelap dengan mudah.
Poin terakhir sekaligus menjawab pertanyaan kedua di atas. Tapi, bukankah Alessandro de’ Medici hidup di Abad Reinasans (Abad ke-14 hingga Abad ke-17) sementara Bridgerton berlatar London di era Regency (awal Abad ke-19)? Jawabannya, kedua periode waktu itu tak terlalu berbeda dalam hal perbudakan dan prasangka sosial diskriminatif terhadap orang non-kulit putih.
Di era kekuasaan Raja George III, termasuk di dalamnya era Regency, perdagangan budak mengalami masa kejayaan. Sekitar 1,6 juta budak diperjualbelikan di Inggris Raya dan koloni-koloninya. Pedagang budak meraup kekayaan berlimpah dari bisnis perdagangan manusia ini (Kamila Shamsie sekali lagi menceritakan ini dengan baik dalam cerpen “Biadab”). Ironisnya, itu terjadi ketika gerakan abolisionisme juga menguat. Ini karena George III adalah penentang keras abolisionisme. Inggris baru sepenuhnya menghapus perbudakan pada 1831, atau sebelas tahun setelah Si Raja Gila itu mati.
Dalam buku Measuring Moment: Strategies of Protest in Eighteenth-Century Afro-English Writing (1988), sejarawan Keith Sandiford menulis, di tengah masyarakat Inggris saat itu, hanya perempuan kulit putih dari kelas-bawah yang bersimpati kepada warga kulit hitam. Selebihnya, terutama masyarakat kelas-atas, menyebut warga kulit hitam dan para mulatto sebagai “monyet”, “jahat”, “berbahaya”, dan “ras yang tercemar”.
Berikut ini kutipan paragraf dari buku tersebut pada halaman 26.
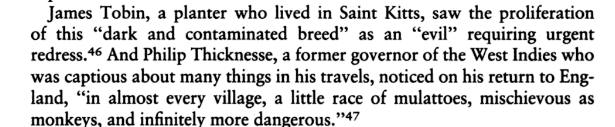
James Tobin, seorang pemilik perkebunan yang tinggal di Santo Kitts, melihat penyebaran “ras gelap dan terkontaminasi” ini sebagai sebuah “kejahatan” yang membutuhkan perbaikan segera. Dan Philip Thicknesse, bekas gubernur Hindia Barat yang suka keberatan terhadap banyak hal dalam perjalanannya, memperingatkan saat kembali ke Inggris, “Di hampir setiap desa, ras kecil mulatto ini, nakal seperti monyet, dan sangat berbahaya.
Maka, segera terlihat ganjil ketika Bridgerton, dalam pesta-pesta dansa dan plesiran kaum aristokrat, menggambarkan kulit hitam berbaur dengan kulit putih, kelas masyarakat yang justru makmur karena penindasan penduduk asli di koloni-koloni dan perdagangan budak.
Persoalannya, seberapa penting akurasi historis bagi sebuah fantasi seperti Bridgerton? Bisakah kita menikmati romansa yang menggemaskan ini sambil menertawakan hipokritas moral tradisi patriarki dan kaum pria kelas-atas Inggris di era Regency (untuk yang satu ini, Bridgerton layak diacungi jempol)?
Jika yang dimaksud dengan “akurasi” adalah hal-hal detail, seperti kostum, properti, atau bahkan kata-kata, menurut saya, itu tak terlampau penting. Tapi, apabila “akurasi” adalah pelajaran dari masa lalu, Bridgerton bisa mengaburkan sejarah. Serial ini terasa mengatakan, “Hei, lihat kulit putih tak pernah menindas kulit berwarna, dan semua baik-baik saja sejak dulu!” Bahkan, di masa kini, gambaran kulit putih di masyarakat tertentu bisa begitu terbuka menerima kehadiran kulit hitam tanpa prasangka masih sulit dibayangkan, terutama ketika kita menyaksikan gerakan BlackLivesMatter di seantero Amerika Serikat pada tahun lalu.
Kepada OprahMag.com, Van Dusen mengatakan ia sengaja memilih aktor kulit hitam sebagai duke dan lady karena ingin serial ini merefleksikan dunia modern saat ini, dimana semua orang dari segala ras bisa berbaur tanpa pertanyaan apa pun. Van Dusen dengan penuh maksud ingin Bridgerton tampil inklusif, dengan menyertakan aktor dari beragam latar belakang.
Tapi, Van Dusen tak konsisten. Dalam Episode 4, terjadi dialog antara Lady Danbury dan Duke of Hastings. Lady Danbury mengatakan, “Lihat ratu kita. Lihat raja kita. Lihatlah pernikahan mereka. Lihatlah akibatnya untuk kita, yang membuat kita bisa menjadi seperti ini. Kita adalah dua masyarakat yang dipisahkan oleh warna kulit, sampai raja jatuh cinta kepada salah satu dari kita. Cinta, Yang Mulia, mengalahkan segalanya.”
Dialog di atas pastinya tak berasal dari novel Quinn sebab Duke of Hastings, dalam novel, digambarkan bermata biru. Quinn juga tidak menampilkan Ratu Charlotte sebagai salah satu karakter utama dalam novelnya.
Dialog di atas menunjukkan Van Dusen yang awalnya mencoba menutup mata terhadap isu ras dan warna kulit tak bisa menahan diri untuk membicarakan itu. Inkonsistensi ini menambah persoalan. Bridgerton—dan dialog tersebut pada khususnya—seakan ingin mengatakan bahwa persoalan diskriminasi rasial bisa selesai—dan telah selesai—pada awal Abad ke-19 hanya dengan sebuah pernikahan meski itu pernikahan teragung di London (antara Raja George III dan Ratu Charlotte).
Pada akhirnya, Anda bisa memilih untuk tidak dipusingkan dengan persoalan edgy tentang ras seperti yang diajukan oleh artikel ini dan menikmati saja fantasi Van Dusen tentang dunia kita “yang baik-baik saja”. Tapi, dengan mengajukan pertanyaan seperti ini, bukankah Bridgerton justru berkontribusi dalam menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang sejarah?[]








