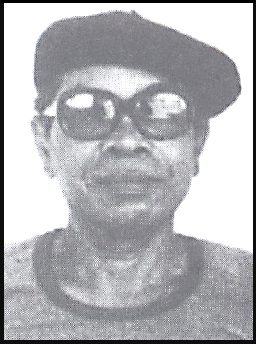Cerpen Nasjah Djamin
Catatan Redaksi: Nasjah Djamin (1924-1997) pengarang dan pelukis asal Sumatera Utara. Dia mengawali karir dengan menjadi ilustrator buku di Balai Pustaka, dan lebih banyak menghabiskan masa kreatif di Yogyakarta. Cerpen ini dinukil dari kumpulan cerpen Di Bawah Kaki Pak Dirman (1967).
SEDANG cerahnya lagi bulan di langit. Begitu bulat dan kuning. Segumpal awan pun tak ada untuk menyembunyikan wajahnya. Dan langit lalu jadi berawan hijau-hijau kebiruan. Bintang-bintang jadi pudar.
Ya, beginilah kesukaanku akhir-akhir ini. Tertelentang di tanah, minta ditekuri bintang-bintang, atau minta diteburi bulan. Rasa luas lapang menyelusuri aku lalu, lapang dan merdeka. Menyatukan sebutir kehadiranku ke dalam rangkuman alam. Selama mengembara di Bali berbulan-bulan lamanya, yang menemani aku ialah bintang, bulan, pasir, laut, dan langit.
Pada malam-malam purnama, aku sering ke pantai Sanur, menggali lubang di pasir yang empuk, lalu menelentang menengadahi bulan bening yang gemuruhi ombak memecah pantai.
Kali ini aku ditekuri wajah bulan, di bawah telapak kaki Pak Dirman! Ya, di telapak kakinya betul. Pak Dirman berdiri menghadap ke barat, begitu berat kelihatan bertatanan di tongkat. Aku telentang di bangku batu sebelah barat, yang mendatari dasar kaki patung. Melentang begitu, aku hanya bisa menangkap dagu Pak Dirman, dan sedikit puncak hidungnya. Selebihnya, langit hijau biru. Bulan amat mesra lembut kini tepat di belakang kepalanya. Terasa seolah-olah penuh kesegaran melintasi ubun- ubun Pak Dirman.
“Jangan genit jeng!” Senyum hatiku. “Melintaslah, dan lagukanlah kelembutanmu di wajah Orang Besar ini.”
Lambat, tapi tak ragu-ragu lagi bulan melintasi ubun-ubun Pak Dirman. Aku tersenyum selama ia merayap. Antara ia dan aku kenal-mengenal dan senyum, sehingga sebulat penuh wajahnya menekuri tengadahku.
“Ai,” katanya lembut senyum. “Kau lagi!”
Aku mengangguk.
Kataku, “Kau makin cantik dan lembut.”
Bulan mencibir dan ketika wajah Pak Dirman dilembutinya, ia mengangguk takzim. Pak Dirman senyum. Perasaan cemburu memahitkan hatiku.
Bulan mekar lagi senyumnya.
“Oh, kau ini!” sesalnya lembut. “Pak Dirman juga Bapakku,” sambungnya.
“Tahu kau?” tanya bulan lagi kepadaku. “Dulu, ketika Pak Dirman digotong oleh anak-anakku melalui rimba, bukit, lembah dan gunung, kami selalu bercakap-cakap. Dan bila ia terbaring, karena dadanya seperti hampa karena penyakit, beliau sangat sedih karena penyakit erat-erat merantai hati dan kakinya. Sedih karena terpaksa menjadi beban digotong kian ke mari, tak bisa leluasa bergerak sebagai orang sehat. Tapi beliau orang besar dan berjiwa besar. Anak-anak cinta kepadanya, bumi Indonesia cinta kepadanya. Dan kau tentu juga cinta kepadanya!”
Aku diam saja. Menengadah.
“Dan kau juga sayang kepadanya.”
Ia telah merayap pelan ke arah Barat.
“Hm, kenapa kau diam?” tanyanya. “Tahu kau? Kau masih ingat, ketika kau menengadah kepadaku seperti sekarang ini? Ya? Ya, waktu itu kau amat lesu, seluruh pasukanmu letih sejak senja melintasi bukit, lembah, hutan, dan menyelusup diam-diam dekat-dekat pos penjagaan tentara Belanda. Kalian satu pasukan ditugaskan ke Jawa Barat, jalan kaki dari Yogya. Dan di tengah hutan rimba yang lebat itu kau menengadah padaku, badanmu kau telentangkan begitu saja di tanah yang basah.
Dan kau berseru padaku, ‘Oh, tunggulah sebentar, jangan lekas-lekas pergi bersembunyi di balik lebat dedaunan.’ Ya, daun-daun rimba yang lebat, tak mengizinkan aku penuh-penuh berhadapan dengan kau. Hanya kita bisa bertemu sekilas di antara daun lebat. Kita berpandangan saling senyum. Waktu kita bertemu itu, baru saja aku melintasi rumah Pak Dirman di Yogya. ‘Lihat-lihatlah anak-anakku di seluruh bagian bumi Indonesla ini, Jeng!’ pesan beliau. Dan aku senang menjumpai setiap kalian. Sebab kalian tidak pernah bertanya untuk apa pergi bertempur. Semuanya datang dari keikhlasan, ikhlas memberi segalanya, juga nyawa.”
“Sudahlah,” kataku.
“Itu sudah lampau.”
Aku memejamkan mata, tak ingin memandangi bulan. Sunyi sebentar. Yang terdengar di sekelilingku, hanya irama dengkur seorang gelandangan yang meringkuk di kaki Pak Dirman sebelah utara.
Ditentang kepalaku, di sebelah kaki Selatan, terdengar dua bocah-bocah berbisik-bisik. Tentu dua bocah gelandangan yang mencari tempat membaringkan badan menunggu pagi besok muncul.
“Pulas kok Min, tidurnya.”
“Tentu dia sedang mimpi dan mengigau,” terdengar jawaban.
Aku memejamkan mata, tak bergerak, dan berbuat pura-pura tidur lelap. Terdengar salah seorang mendekati, dan terasa ia takut-takut menekuri wajahku. Aku tahu bila mata kubuka, tentu wajahnya akan kulihat melindungi bulan.
“Heran, priyayi muda ganteng kok tidur seperti gelandangan,” kata bocah itu menekuri wajahku, sambil duduk kembali di selatan dekat temannya.
Dalam hati aku tertawa. Tapi aku diam tak bergerak.
“Barangkali dia berkelahi dengan raden ayunya?” tanya yang seorang.
“Atau banyak hutang, dan lari bersembunyi.”
Terdengar tertawa mereka. Sebuah suara tawa yang jernih, dan sebuah lagi yang mulai serak. Dan setelah agak reda, terdengar suara yang nyaring berkata, “Biarpun ia berkelahi dengan raden ayunya, atau banyak hutang, tapi ia menyerobot tempat tidurku. Aku sudah mengantuk betul.”
“Nanti dia akan bangun juga,” kata suara yang agak serak membujuk.
“Tapi tengah malam begini aku harus duduk di kaki barat.”
“Nah, kamu ini! Percaya tahyul.”
“Ini malam Jum’at Kliwon, to, Kang?”
“Lha, iya, kenapa?”
“Aku harus duduk di kaki barat setiap malam Jum’at Kliwon.”
Terdengar suara yang serak tertawa, membodoh-bodohkan si suara nyaring.
“Apa bisa menolong, Dik?”
Si suara nyaring terdiam.
“Sudah berapa bulan kau duduk setiap malam Jum’at Kliwon di kaki barat, he? Apa hasilnya? Kamu tetap jadi ‘kere’ gelandangan. Meminta kok kepada patung Pak Dirman!”
Lalu kemudian dengan suara rendah katanya, “Priyayi tukang serobot ini tentu banyak duit di kantongnya. Lah, kenapa tidak kita ambil sedikit?”
“Apa kau berani, Kang?”
Tak ada jawaban. Lama aku menunggu jawaban. Entah berapa lama.
Tapi akhirnya terdengar si suara serak mengeluh, “Aku mengantuk, lebih baik tidur saja.”
Terdengar ia merebahkan diri, yang kemudian disusul lagi oleh suara tubuh merebah, tentunya si suara nyaring ikut membaringkan diri.
Mataku kubuka pelan-pelan. Bulan tak menekuri tepat-tepat lagi kini. Ia entah telah berapa derajat bergeser sudah ke barat. Terpaksa kutelengkan kepala ke arahnya.
“Kenapa kau diam?” tanya bulan. “Aku tahu kau tidak tidur!”
Aku mengangguk, dan sambungnya, “Kau masih sakit hati dan cemburu?”
Aku mencibir, teringat si suara nyaring yang menyebut aku tukang serobot.
Bulan tersenyum, “Kau orang aneh,” katanya. “Waktu dulu, kita bertemu di Sanur, kemudian di Ubud, dan di Batubolong, kau bertanya kepadaku, ‘Jeng, apakah kau harus melintas di Malioboro, dan di Gunung Kidul? Apakah kau Bulan? Apakah Bulan di Yogya dan Bulan di Gunung Kidul sama dengan Bulan di Sanur dan di Ubud?’ Kau betul-betul anak edan. Aku sedih kau buat, waktu di Bali itu. Kau ingat? Kau meneguk arak sebotol di pantai Sanur, dan kau berteriak, Kau bukan Bulan yang kukenal di Yogya atau di Gunung Kidul, kau Bulan Bali!”
“Maafkanlah aku sekali ini,” kataku malu. “Aku tak ingat diri waktu itu.”
“Ya tentu,” katanya lembut. “Aku mengerti kemarahanmu waktu itu. Kau ingin bercakap-cakap dengan aku di Ubud waktu malam bulan Purnama. Tapi waktu itu hujan turun sejak senja, dan mendung tebal tujuh lapis menghalangi aku. Aku mengerti kemarahanmu di Sanur ketika aku muncul dari laut sehabis masa-masa purnama!”
“Sekali lagi maafkanlah aku Jeng.”
Bulan senyum lembut dan baik.
Katanya, “Aku tak apa-apa. Tapi nasihatku kepadamu, bila besok-besok kau minum, ajaklah aku minum.”
“Kau tahu,” tanyanya lagi. “Entah kapan itu terjadi, aku sudah lupa. Aku kenal seorang penyair besar di tanah Cina sana. Syair-syairnya dikenal oleh rakyat, dan menjadi nyanyian rakyat. Ia seorang yang lembut dan hormat. Aku sering diajaknya minum. Bila aku tersenyum kepadanya, ia menuangkan anggur ke seloki, lalu kami mendentingkan seloki dan minum bersama-sama. Kami bercakap-cakap sambil minum semalam suntuk, hingga ia meminta diri. Aku ingin kau mau menawarkan aku minum seperti dia.”
“Tapi aku jarang minum anggur Jeng, terlalu mahal. Aku cuma bisa menawarkan kepadamu arak atau tuak.”
“Itu tak menjadi soal. Aku kepingin kau ajak minum. Ha, kurasa kau juga kenal kepada penyair tanah Cina yang besar itu?”
“Ya,” jawabku dengan gairah. “Aku kenal. Dan aku pernah mendengar bahwa kau dan dia sering minum anggur. Penyair yang beruntung dia, Li Tai Po itu!”
“Ya,” kata si Bulan. “Aku tahu, bahwa orang-orang yang tengah bercinta selalu menengadah kepadaku. Orang-orang rindu dan kangen ingin bercakap-cakap dengan aku. Kulihat kau sekarang tak perlu kepadaku. Dulu di Bali kau selalu setia menunggu aku ke luar, karena kau sedang kangen.”
“Sekarang tak ada yang kurindukan lagi,” kataku senyum compang-camping.
“Ya, aku tahu! Kau patah hati sekarang, dan pahitmu amat pekat.”
“Tidak! Aku tidak patah hati.”
“Jangan bohongi dirimu! Bila aku yang kau bohongi tak apalah, tapi aku sudah tahu.”
“Tapi jangan dikira aku patah hati Jeng! Hatiku sekasar batu, mana mungkin patah? Aku tidak patah. Tidak bisa patah, tidak bisa patah hati!”
Aku menutup mukaku dengan lengan, tak ingin melihat wajah Bulan.
“Dia mengingau lagi Kang!” terdengar suara nyaring di sebelah selatan. “Apakah yang patah Kang?”
“Hatinya, Lik!”
“Lha, kok hati bisa patah?”
“Ah, kamu ini bodoh! Kamu masih bocah, belum tahu bercinta-cintaan.”
Si suara nyaring mengeluh, dan terdengar ia mengenakkan ringkuk tidurnya.
“Na, kau tentu membenci aku sekarang,” terdengar suara Bulan.
“Tidak,” kataku pelan. “Aku tak membenci apa pun dan siapa pun.”
“Aku tahu, kau sekarang benci kepada dirimu, karena kau melihat dirimu telanjang bulat dan takut mengakuinya?”
Aku mengangguk di balik lingungan lenganku.
“Aku senang kau mau berkuat hati,” kata Bulan kemudian. “Dan aku tahu, bahwa kau mengharap-harapkan dia. Tapi itu soalmu, dan baik bahwa kau masih memiliki harapan. Artinya kau tak putus harap untuk hidup. Kau tidur?” tanyanya ketika aku tak bergerak dan tak bersuara.
“Baiklah, tenangkanlah hatimu dan carilah kekuatan mengatasi kekecewaan hidup. Selamat malam.”
Kemudian setelah aku menggumam selamat malam kepadanya, terdengar suara Bulan takzim mengucapkan selamat malam kepada Pak Dirman. Juga pelan tertegun mengucapkan selamat malam kepada orang-orang yang berbaring di sekitar kaki Pak Dirman.
Entah berapa lama aku menyelinap antara tidur dan jaga. Tapi aku sadar kembali ketika mendengar suara nyaring berkata, “Bulan ditutup awan, Kang!”
“Huhh,” keluh si suara nyaring itu bersuara pula, “Kang, Kang! Priyayi itu kok belum bangun-bangun?!”
Terdengar si suara parau menggerutu dan menyentak dalam tidurnya.
“Aku perlu duduk di kaki barat Kang!”
Terasa olehku, si suara nyaring duduk menyandar, dan kemudian si suara parau.
“Kamu ini anak bodoh,” si suara parau mengomeli. “Duduk di kaki selatan saja sama, to?”
“Bangku yang di sebelah barat adalah tempat tidurku; tempatku setiap malam Jum’at Kliwon! Aku perlu duduk di situ.”
“Bodoh,” omel si suara parau dalam mulut.
Senyap kemudian. Aku berpura-pura tidur lelap, merasa bersalah menyerobot tempat tidur mereka.
“Apa saya bangunkan dia?” tanya si suara parau.
“Oh, jangan. Nanti Kakang dipukuli.”
“Ya, sudah! Jangan menggerutu.”
Lalu, lama pula sunyi. Sudah tergerak hatiku akan bangun dan menggeliat, lalu menyerahkan tempat yang kuserobot.
Tapi tiba-tiba dengan pelan si suara nyaring berkata, “Aku cuma menjalankan pesan Ibu, Kang. Kakang tak ada, waktu Ibu meninggal. Cuma aku yang menunggui Ibu. Kakang sedang mencari telor. Waktu itulah Ibu meninggalkan pesan Kang!”
“Ah, kamu ini. Apa pesan Ibu? Ibu bilang, bahwa bapak kita pernah ikut menggotong tandu Jenderal Sudirman dari kampung ke kampung, dari bukit ke bukit? Bahwa bapak tidak pulang, cuma menitipkan pesan kepada kawannya yang sama-sama ikut menggotong sampai ke desa lain, bahwa bapak telah memutuskan akan ikut dengan rombongan Pak Jenderal, ikut terus berjuang? Lik, Lik! Cerita ini aku sudah tahu. Dan aku juga sudah tahu bahwa bapak tidak pernah pulang, cuma kawannya yang mengabarkan bahwa ia sudah tewas.”
“Apa bapak juga tentara Kang?”
“Tidak Lik, bapak kita bukan tentara. Cuma orang desa biasa, yang sukarela menggotong tandu Pak Dirman. Aku mendengar, ia cuma diminta membantu ikut menggotong sampai ke desa di seberang bukit. Tapi bapak berkeras mau ikut terus dengan pasukan.”
“Tapi bapak seorang Pahlawan, Kang!”
“Tentu, bapak Pahlawan!”
Aku menahan napas. Di antara dua orang itu, diam sepi. Aku teringat, ketika pasukan kami berlong-mars dari Yogya merembes ke Jawa Barat. Bagaimana orang-orang desa yang kami lewati, senantiasa terbuka dan sukarela membantu dan menyambut setiap pasukan yang datang dan yang pergi. Bagaimana mereka menyediakan diri sebagai penunjuk jalan, melalui bukit dan gunung. Bagaimana mereka senantiasa siap dengan dapur umum, baik siang maupun malam untuk pasukan-pasukan yang datang melepaskan lelah.
Ya, mereka, orang-orang desa terpencil di bukit-bukit, pahlawan-pahlawan tak bernama yang tak pernah disebut-sebut. Tentu sama kejadiannya dengan bapak suara serak dan si suara nyaring di sebelahku ini!
“Kata Ibu, Bapak sama Pahlawannya dengan Pak Jenderal Sudirman,” terdengar si suara nyaring berkata dengan pelan.
“Tentu,” kata si suara parau. “Tapi kita waktu itu masih kecil, baru tahu merangkak. Kalau Ibu bilang begitu, tentu betul.”
“Ya, tentu betul Kang.”
“Ha, apa pesan Ibu kepadamu, he?”
“Tidak ada yang penting Kang. Cuma buat aku sendiri saja.”
“Ah, kamu ini! Coba, pesan apa?”
Lama si suara nyaring tak menyahut.
Dan tiba-tiba si suara nyaring itu mengerang, gumamnya, “Perutku mulas lagi, Kang.”
“Tidur diam-diam saja, Lik. Tadi masih ada darahnya?”
Si suara nyaring itu mengerang, “Darah semua Kang, darah.”
“Tahankan saja, Lik. Nanti sembuh sendiri.”
“Dulu aku juga pernah berak darah. Besok akan aku petik buah sirsak yang di halaman rumah Kanjeng Wetan Beteng itu. Sirsak yang hampir masak, kalau kau makan dua buah, berak darahmu pasti sembuh.”
Lalu, suara si parau lagi dengan pelan, “Aku kepingin mengambil uang sangu dari kantong priyayi yang tidur-tiduran di sebelah!”
Terdengar ia mendekati, tapi tak berani menyentuh aku yang berpura-pura tidur nyenyak. Kalau ia merogoh kantongku, akan kurelakan! Di saku hemku cuma ada sejumlah empatpuluh satu rupiah, sisa beli rokok. Aku ingin memberikannya kepada mereka, tapi ini tak bisa kulakukan begitu saja. Di saku belakang celanaku masih ada selembar limapuluhan.
Lalu terdengar keluh si suara parau. Tak terasa bahwa yang di saku hemku telah menjadi miliknya. Begitu cepat! Aku memuji kepintarannya dalam hati. Dan dengan tenang, seolah-olah tak ada terjadi apa-apa, ia duduk di dekat si suara nyaring.
“Sakitmu bagaimana sekarang Lik?” tanyanya pelan.
“Sudah mulai hilang perihnya, Kang.”
Lalu lama pula mereka bersembunyi diri. Aku melihat kepada Bulan dari celah-celah sipit mataku. Ia senyum mengangguk, katanya, “Kau orang edan yang baik.”
“Kau tidak di rumah waktu itu, Kang!” terdengar si suara nyaring pelan.
“Kapan?”
“Waktu Ibu meninggal. Kau cari telor ke bukit wetan. Ibu bilang kepadaku, ‘Lik, jangan sedih, kita orang melarat. Ibu tidak bisa memberikan kau dan Kakangmu makanan nasi. Tapi Bapakmu mati sebagai Pahlawan, Lik! Dia ikut memikul tandu Pak Jenderal Dirman. Di rumah yang reyot ini Pak Jenderal pernah menginap.’”
“Ya,” sela si suara parau. “Aku masih ingat. Aku dilarang Ibu ribut-ribut, aku menangis melihat banyak prajurit tegap-tegap di rumah dan di halaman. Kau masih belum bisa berjalan Lik!”
“Ibu juga mengatakan begitu. Aku amat kurus, kata Ibu. Pak Dirman melarang ibu repot-repot, dia cuma mau beristirahat sebentar. Tapi Ibu diam-diam membuat bubur untuk Pak Dirman yang sakit. Ibu amat takut gemetar, ketika membawa bubur itu kepada Pak Dirman, takut dimarahi. Tapi Pak Jenderal senyum, dan kemudian air matanya jatuh. Katanya, ‘Ah Mbok ini bagaimana?’ Kata Ibu aku di gendongan Ibu, menyusu, tapi aku amat iba melihat Pak Dirman. ‘Kenapa susah-susah begini Mbok?’ kata Pak Dirman. ‘Bayi sampeyan ini lebih perlu makan bubur yang enak!’ Lalu disendoknya bubur sesendok, disuapkannya kepada saya, Kang! Ibu menangis, dan Pak Dirman bilang, ‘Jangan menangis, Mbok! Lihat, saya makan bersama bayi Mbok. Semoga Tuhan memberkahi dan melindunginya.’ Kata Ibu, aku lalu tertawa, memegang bibir Pak Jenderal.”
Sejenak si suara nyaring diam. Bulan senyum lirih kepadaku, katanya jauh, “Kau lihat? Tiap manusia mempunyai luka dan dera.”
“Lantas apa Lik?” tanya si suara parau.
“Bapak memarahi Ibu karena mengganggu Pak Jenderal, lalu menyuruh bawa aku ke luar. Tapi Pak Jenderal senyum saja.”
“Itu saja.”
“Lalu Pak Jenderal mencium aku, Kang! Dan Ibu tersedu-sedu ke luar.”
“Lalu itu saja?”
“Ya, itu saja Kang. Tapi Pak Jenderal lalu bilang sama Ibu, ‘MBok! Kalau besok perang sudah habis, dan bayimu sudah besar, datanglah bertamu ke rumah saya di Yogya.’ Kang! Waktu Ibu mau meninggal, Ibu sampaikan pesan Pak Jenderal, dan aku berjanji akan menemui Pak Jenderal.”
“Lik, Lik! Pak Jenderal sudah wafat Lik!”
“Tapi dia bilang kepada Ibu, Kang. Aku diundang oleh Pak Jenderal.”
“Dia sudah tidak ada, Lik. Ini cuma patungnya, cuma batu. Pak Jenderal dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki.”
Aku teringat tiba-tiba kepada penduduk desa-desa yang kami singgahi, waktu pasukan kami merembes ke Jawa Barat dari Yogya. Kepada desa-desa yang kami makan berasnya, kami tiduri ambennya, kami minum airnya! Kepada penduduk desa yang aku sudah tak tahu entah di pegunungan mana, bukit mana, atau di lembah mana. Tapi untuk pasukan yang lewat, mereka tetap menyediakan nasi ompreng; tetap menjadi penunjuk jalan ke perbatasan lain, semuanya terjalin dalam satu tekad dan satu tujuan perjuangan! Dan aku teringat, ketika Pak Lurah menemui Kepala Pasukan kami, dan dengan amat hormat menanyakan apakah dapur umumnya bisa mendapat bantuan kadarnya dari pasukan. Tapi pasukan kami tidak membawa uang. “Pak,” kata Pak Lurah, “Penduduk desa sendiri kadang-kadang cuma satu kali makan sehari, mereka kurus dan selalu sakit malaria atau busung lapar.” Dan aku ingat, Kepala Pasukan kami menuliskan secarik bon dan membubuhi cap pasukan. “Pak, datanglah dan tukarkan bon ini di Kementerian Pertahanan di Yogya,” kata Kepala Pasukan. Dan Pak Lurah mengangguk, wajahnya tak berkerut, ketika bon itu disusunnya rapi-rapi di atas tumpukan yang tebal dari bon-bon pasukan yang lebih dahulu dari kami mampir di situ. Dan Pak Lurah berkata, “Inggih, matur nuwun. Selamat berjuang. Merdeka!” Aku tak tahu apakah bon-bon setebal bantal di desa itu pernah terbawa ke Yogya, sebab beberapa bulan kemudian Yogya sudah diduduki oleh Belanda.
“Sekali waktu aku akan bertemu dengannya Kang, bertemu dengan Pak Jenderal.”
“Ha, kamu ini!”
“Setiap malam Jum’at Kliwon aku duduk di barat, di kakinya.”
“Hss! Bodoh kamu. Ini cuma patung Pak Dirman. Orang mati tidak bisa ditemui Lik! Tidak boleh meminta apa-apa kepada orang yang sudah meninggal. Doakanlah kepada Tuhan agar amal Pak Dirman diterima, dan arwahnya mendapat tempat yang baik!”
“Sekali waktu pasti aku bertemu dengannya Kang. Dia pernah mencium aku, dan mengundang aku ke Yogya.”
“Keras kepala dan bodoh.” Lalu dengan suara menyesal, “Huh, kamu mencret lagi! Oalah baunya! Mambunya! Pergi berak ke sana dan cuci di kolam. Hati-hati jangan kelihatan orang!”
Si suara nyaring bersingut, melewati kepalaku dan mencuri-curi jongkok di kolam di hadapanku. Baunya menyemai ke mana-mana. Dalam cahaya bulan yang sudah agak memudar, kulirik diam-diam bentuk badan bocah kurus di tepi kolam itu. “Tuhan,” keluhku. Dan ketika aku berpandangan dengan Bulan, senyum lembutnya amat perih.
“Ya,” keluhnya lirih.
“Ia masih bocah cilik dan layu sebelum tumbuh!”
Dan tiba-tiba saja tidur malam dikejuti oleh derai ketawa di kolam.
Seorang gelandangan bertubuh bulat melantingkan batu ke air kolam. Air memancar sepeda dekat si suara nyaring mencangkung. Aku tertunduk.
Si badan bulat terbahak-bahak.
“Oalahl Oalah!” serunya menyentak-nyentak. “Anak Pahlawan berak! Anak Pahlawan berak! Oalah! Ojo dumeh Lik, nanti Pak Dirman mambu busuk?”
Si suara nyaring berdiri. Pelan. Lalu pelan mendekati si badan bulat. Sikapnya pasti dan nekat. Si badan bulat terbahak terus, meremehkan.
“Ho, ho! Jangan dekat, kau mambu?”
“Kau bilang apa? Ha?”
“Masa kamu tidak dengar! Aku bilang, kamu anak Pahlawan berak!”
“Jangan hina saya?”
“Lha, Bapakmu kan Pahlawan! Kamu anak Pahlawan? Pahlawan ngising.”
“Jangan hina saya! Jangan hina Bapak saya?”
“Kan kau mengaku Bapakmu Pahlawan?”
“Bapak saya memang Pahlawan, Pak Dirman pernah digotongnya di tandu!”
“Ha, ha! Pahlawan ngising!”
Tiba-tiba, secepat kilat si suara nyaring menubruk si badan bulat.
“Bangsat! Bangsat!” jeritnya. Tangannya yang kurus memukuli si badan bulat. Mereka berguling di tepi kolam. Si badan bulat bukan imbangan si suara nyaring. Sebelum aku sadar, dan hendak menengahi, tiba-tiba Kakang si suara nyaring, telah meloncat dan menghantam si badan bulat, hingga terjajar beberapa meter.
“Rasain kowe!” pekiknya. “Berani cuma sama anak kecil.”
Si badan bulat tiba-tiba menangis, bertubi-tubi dihujani pukulan si Kakang. Ia berteriak-teriak meminta ampun. Dan ketika ia dilepaskan, ia lari memaki-maki dalam tangisnya.
Dan tiba-tiba si Kakang terpana, melihat aku di hadapannya. Si suara nyaring dirangkulnya, sebagai hendak melindungi. Wajahnya begitu ketakutan. Tahu bahwa ia telah berbuat salah, menyambar uang dari sakuku. Pencurian yang kurelakan! Aku senyum.
“Tidak baik berkelahi sama teman,” kataku. “Ini adikmu?”
Ia mengangguk, dan kian mempererat rangkulan adiknya yang diam terisak-isak.
“Begitu kurus,” kataku. “Belum makan?”
Oh, pertanyaan yang konyol dan pahit!
“Sudah, sana,” kataku menggembirakan suara. “Kamu mengganggu saya tidur saja.”
Hatiku iba menjadi-jadi! Kataku, “Ini! pergi cari makanan. Ini uang!”
Dan uang limapuluhan yang di kantong belakang celana kugenggamkan ke tangan si Kakang. Besok, aku masih bisa ngebon honorarium di kantor Redaksi Majalah, terlintas di hatiku!
“Matur nuwun, Pak. Nuwun!” kata si Kakang.
Aku tertawa lebar saja. Kupandangi mata si suara kecil yang masih berair, matanya yang begitu lirih dan nelongso!
“Sudah. Cari makan sana buat adikmu!” kataku.
Mereka pergi pelan-pelan. Sekali dua kali si Kakang masih menoleh kepadaku, menoleh kepada priyayi tolol yang kemalaman di kaki Pak Dirman!
Ketika aku menengadah langit aku menengadah ke wajah Pak Dirman. Ia tersenyum. Bulan yang hampir bertengger di atap gedung kota sebelah barat, juga tersenyum.
Hingga subuh aku mengukur Malioboro.
Ketika aku lewat beberapa kali di depan patung Pak Dirman, dari jauh kulihat sosok tubuh si suara nyaring duduk bersila, di bekas tempatku tidur, dan si Kakang meringkuk di sebelahnya.
Tapi setelah pukul tujuh aku bergegas ke tempat pekerjaanku, banyak orang berkerumun di kaki patung Pak Dirman.
Berita koran esok harinya memuat kabar kota, beberapa baris, “Seorang bocah gelandangan kedapatan mati di kaki patung Pak Dirman.”
Apakah patung itu mengetahuinya, atau Bulan yang menjelang fajar? Hanya Tuhanlah Yang Maha Tahu.[]
[Dinukil dari: Nasjah Djamin, Di Bawah Kaki Pak Dirman, (Jakarta: Balai Pustaka), 1986, hlm. 32-45]